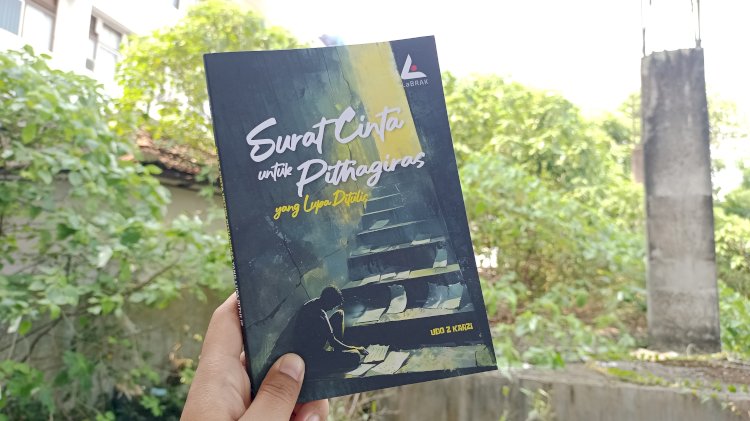Oleh Liviyanti Mega Ayunita
NOVEL Surat Cinta untuk Pithagiras yang Lupa Ditulis (Pustaka LaBRAK, 2024) dapat dibaca sebagai upaya Udo Z Karzi menulis kembali pengalaman generasi kampus bukan semata sebagai sejarah aksi, melainkan sebagai sejarah afeksi: cinta, kehilangan, rasa bersalah, dan pengkhianatan terhadap idealisme. Politik tidak hadir sebagai kronik demonstrasi, tetapi sebagai getaran batin tokoh-tokohnya. Dalam konteks ini, novel bergerak di wilayah yang jarang disentuh secara serius: pertautan antara gerakan mahasiswa, relasi intim, dan persoalan gender. Namun, justru di sanalah kekuatan sekaligus problem estetik-ideologis novel ini.
Membaca novel ini akan lebih utuh jika diletakkan dalam lanskap gerakan mahasiswa Lampung tahun 1990-an. Periode ini ditandai oleh menguatnya kembali aktivisme kampus setelah fase pembekuan politik 1980-an. Gerakan tidak hanya muncul dalam bentuk demonstrasi, tetapi tumbuh sebagai ekosistem wacana dan praktik. Pers mahasiswa memainkan peran penting sebagai medium produksi kesadaran, penyebaran isu, sekaligus ruang latihan ideologis. Buletin, tabloid kampus, dan selebaran stensilan menjadi “senjata” yang relatif aman sekaligus rawan: aman karena bergerak di wilayah kultural, rawan karena selalu dibayang-bayangi sensor, pembredelan, dan represi administratif.
Seiring itu, kelompok-kelompok studi bermunculan sebagai dapur intelektual gerakan. Diskusi rutin di sekretariat, kos-kosan, atau warung kopi membedah teori sosial, kritik pembangunan, demokrasi, feminisme, hingga sastra perlawanan. Kelompok studi bukan sekadar ruang belajar, tetapi juga ruang pembentukan subjek: tempat aktivis menempa bahasa politik, etika kolektif, dan imajinasi tentang perubahan. Dari sinilah banyak aktivis pers dan lapangan lahir, dengan watak gerakan yang cenderung reflektif, cair, dan penuh perdebatan internal.
Di sisi lain, “parlemen jalanan” menjadi wajah paling kasatmata dari gerakan. Mimbar bebas, teatrikalisasi, long march, dan pendudukan ruang publik menjadikan jalan sebagai arena artikulasi politik alternatif. Di Lampung, jalan bukan hanya ruang konfrontasi dengan negara, tetapi juga ruang negosiasi identitas: antara mahasiswa, rakyat kota, aparat, dan jaringan kekuasaan lokal. Di sinilah tubuh aktivis diuji, bukan hanya oleh kekerasan fisik, tetapi juga oleh kelelahan, rasa takut, euforia kolektif, dan solidaritas yang rapuh.
Latar ini penting karena novel Surat Cinta untuk Pithagiras yang Lupa Ditulis tidak lahir dari ruang hampa. Ia menyerap denyut gerakan yang berlapis: kerja sunyi pers mahasiswa, militansi intelektual kelompok studi, dan teatrikalitas parlemen jalanan. Dengan menempatkan kisah cintanya di dalam ekosistem itu, Udo Z Karzi menulis generasi yang hidup dalam persilangan antara ide, tubuh, dan afeksi—sebuah generasi yang bagi mereka, politik bukan hanya agenda, melainkan cara hidup.
Subjek yang Rapuh
Dalam konteks Lampung 1990-an, gerakan mahasiswa yang direkam novel ini juga penting dibaca sebagai jejaring praktik yang beragam: pers mahasiswa, kelompok-kelompok studi, hingga apa yang kerap disebut sebagai “parlemen jalanan”. Aktivisme tidak hanya berlangsung dalam demonstrasi besar, tetapi juga dalam kerja sunyi: diskusi panjang di sekretariat pers kampus, penerbitan buletin stensilan, forum-forum kecil yang membedah Marxisme, humanisme, atau teologi pembebasan, serta mimbar bebas di sudut-sudut kota. Novel ini menangkap atmosfer itu sebagai lanskap keseharian: gerakan sebagai ritme hidup, bukan hanya sebagai ledakan peristiwa.
Dari perspektif gerakan mahasiswa, novel ini menegaskan bahwa aktivisme bukan hanya soal tuntutan, tetapi juga soal subjek yang rapuh. Tokoh-tokohnya tidak dipahat sebagai pahlawan, melainkan sebagai manusia yang goyah, mencintai, cemburu, takut, dan sering kali lelah. Kampus tidak hanya hadir sebagai ruang produksi kesadaran, tetapi juga sebagai ruang disiplin: rapat yang tak selesai-selesai, jargon yang menua, dan solidaritas yang mudah retak. Udo berhasil memanusiakan gerakan. Udo berhasil memanusiakan gerakan dengan menunjukkan bahwa di balik pamflet, buletin, dan spanduk selalu ada tubuh yang letih dan hati yang terluka.
Namun, justru karena terlalu terikat pada psikologi tokoh, novel ini cenderung menggeser gerakan dari wilayah politik struktural ke wilayah moral personal. Pers mahasiswa lebih tampil sebagai ruang curhat generasi, kelompok studi sebagai latar intelektual yang murung, dan parlemen jalanan sebagai panggung eksistensial, bukan sebagai perangkat politik dengan logika, strategi, dan relasi kuasa yang spesifik. Konflik besar sering direduksi menjadi konflik batin. Kegagalan kolektif jarang dibaca sebagai persoalan organisasi, kooptasi wacana, atau fragmentasi antar-jenis gerakan, melainkan sebagai tragedi etis individu. Akibatnya, gerakan mahasiswa lebih tampak sebagai drama kesadaran daripada arena pertarungan politik yang konkret.
Relasi Cinta yang tidak Netral
Di titik inilah perspektif feminisme menjadi penting. Novel ini justru paling hidup ketika berbicara tentang tubuh dan suara perempuan dalam ruang aktivisme. Tokoh-tokoh perempuannya tidak diposisikan sekadar sebagai “pendamping pejuang”, tetapi sebagai subjek yang mengalami tekanan berlapis: sebagai aktivis, sebagai kekasih, dan sebagai perempuan dalam struktur patriarki. Relasi cinta digambarkan tidak netral, tetapi selalu berkelindan dengan hierarki organisasi, kharisma politik, dan legitimasi intelektual. Dalam novel ini, ranah personal benar-benar politis. Dalam ruang pers mahasiswa, kelompok studi, maupun parlemen jalanan, tubuh perempuan digambarkan tidak pernah netral. Ia menjadi medan kerja, simbol moral, sekaligus objek kontrol. Novel ini menunjukkan bagaimana perempuan sering memikul beban ganda: memproduksi wacana, merawat jaringan, sekaligus menanggung ekspektasi afektif dan kultural yang tidak dialami setara oleh aktivis laki-laki.
Udo dengan cukup berani menyingkap kekerasan simbolik yang sering dinormalisasi dalam gerakan: pembagian kerja berbasis gender, romantisasi pengorbanan perempuan, hingga tubuh perempuan yang menjadi arena konflik ideologis dan emosional. Perempuan dihadirkan sebagai pengingat bahwa gerakan tidak hanya berhadapan dengan negara, tetapi juga dengan patriarki yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. Di sinilah novel ini menawarkan kontribusi penting: ia memperlihatkan bahwa kegagalan gerakan tidak hanya lahir dari represi eksternal, tetapi juga dari ketidakmampuan mereformasi relasi internal.
Meski demikian, feminisme dalam novel ini belum sepenuhnya menjadi kerangka utama. Ia lebih sering muncul sebagai lapisan tematik, bukan sebagai lensa struktural yang menata keseluruhan konflik. Tokoh-tokoh perempuan kuat memang dihadirkan, tetapi jalur politik mereka kerap berhenti pada penderitaan, bukan pada artikulasi agenda atau praksis perlawanan yang mandiri. Feminisme lebih berfungsi sebagai kritik moral ketimbang sebagai posisi ideologis yang radikal. Selain itu, representasi perempuan masih didominasi pengalaman kelas menengah intelektual; suara perempuan dari latar sosial lain, termasuk perempuan Lampung dengan kompleksitas budaya lokalnya, relatif belum dieksplorasi secara maksimal.
Arsip Emosi Gerakan
Secara estetik, gaya liris Udo memperkuat kesan bahwa novel ini adalah arsip emosi gerakan. Bahasa puitik, struktur nonlinier, dan kecenderungan reflektif menjadikan novel ini lebih dekat pada elegi ketimbang manifesto. Ini memperkaya pengalaman membaca, tetapi sekaligus mempertegas bahwa yang diwariskan bukan peta politik, melainkan ingatan dan luka. Novel ini bekerja sebagai ruang kontemplasi: tentang apa yang tersisa dari gerakan ketika slogan-slogan telah memudar.
Dengan demikian, Surat Cinta untuk Pithagiras yang Lupa Ditulis dapat dibaca sebagai novel tentang kegagalan yang produktif. Ia gagal menjadi analisis gerakan yang tajam, tetapi berhasil menjadi kritik kultural tentang bagaimana gerakan dijalani, dicintai, dan ditinggalkan. Dari sudut feminisme, novel ini membuka celah penting untuk membaca ulang aktivisme sebagai ruang yang sarat relasi kuasa gender. Dari sudut gerakan mahasiswa, novel ini mengingatkan bahwa politik tanpa refleksi etis dan kesadaran tubuh hanya akan mereproduksi dominasi dalam bentuk lain.
Pada akhirnya, novel ini bukan ajakan untuk kembali ke jalan, melainkan ajakan untuk menimbang ulang apa arti “perjuangan”. Ia menggeser pertanyaan dari “apa yang kita tuntut?” menjadi “siapa yang kita lukai, siapa yang kita bungkam, dan siapa yang kita cintai dalam proses menuntut itu?”. Dalam konteks sastra Indonesia kontemporer, terutama sastra yang bersinggungan dengan sejarah gerakan, posisi ini menjadikan karya Udo Z Karzi penting: sebagai pengganggu romantisme aktivisme dan sebagai pintu masuk untuk membaca gerakan dari perspektif tubuh, gender, dan ingatan. (*)
Data Buku
Judul: Surat Cinta untuk Pithagiras yang Lupa Ditulis
Penulis: Udo Z Karzi
Penerbit: Pustaka LaBRAK, Bandar Lampung
Cetakan: I, Juni 2024
ISBN: 978-623-5315-13-3
Tebal: x + 166 hlm, 13 x 19 Cm
_____________
Liviyanti Mega Ayunita, jurnalis, alumnus FISIP Universitas Lampung.